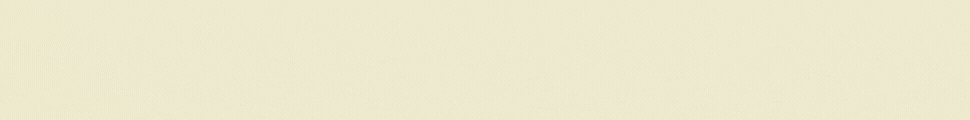Dalam sejarah Batavia akhir abad ke-19, nama Si Pitung muncul bukan pertama-tama sebagai pahlawan, melainkan sebagai bandit pribumi dalam arsip pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun, bagi masyarakat Betawi, ia dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial pada masa kolonial.
Si Pitung diperkirakan lahir sekitar tahun 1860 di daerah Rawabelong, kawasan pinggiran Batavia yang saat itu dihuni petani, santri, dan buruh kebun. Nama aslinya diyakini Salihoen atau Saleh, anak dari pasangan petani kecil yang hidup dalam tekanan ekonomi akibat sistem pajak, sewa tanah, dan dominasi tuan tanah partikelir.
Sejarawan Jakarta mencatat bahwa Batavia kala itu adalah kota dengan kesenjangan sosial yang tajam. Orang Eropa dan elite Tionghoa menguasai tanah dan modal, sementara pribumi—termasuk orang Betawi—sering menjadi korban eksploitasi. Dalam kondisi seperti ini, muncul figur-figur “jagoan kampung”, yakni individu yang menggunakan kekuatan fisik dan jaringan sosial untuk melindungi komunitasnya, sekaligus menantang aparat kolonial.
Si Pitung tumbuh sebagai santri dan dikenal menguasai ilmu silat dan pengetahuan agama. Catatan lisan menyebut ia sering merampok rumah tuan tanah dan saudagar kaya, lalu membagikan sebagian hasilnya kepada orang miskin. Namun, arsip kolonial tidak mencatat pembagian ini—yang tercatat hanyalah serangkaian perampokan, penyerangan, dan pengejaran oleh polisi kolonial (marechaussee).
Bagi pemerintah Hindia Belanda, Si Pitung adalah ancaman terhadap ketertiban dan hukum kolonial. Ia diburu selama bertahun-tahun, tetapi selalu lolos, yang kemudian melahirkan cerita tentang kesaktiannya—konon kebal peluru dan memiliki jimat. Sejarawan memandang kisah kesaktian ini sebagai bentuk mitologisasi rakyat, lazim dalam masyarakat tertekan yang membutuhkan figur simbolik untuk melawan kekuasaan.
Akhirnya, pada tahun 1893, Si Pitung ditembak mati oleh aparat Belanda di daerah Kebon Jeruk. Versi resmi menyatakan ia tewas dalam baku tembak. Versi rakyat menyebut ia gugur karena dikhianati atau ditembak dengan peluru emas—sebuah metafora bahwa kekuatan kolonial hanya bisa mengalahkannya dengan cara “tidak biasa”.
Bagi sejarawan Jakarta, Si Pitung bukan sekadar pahlawan atau penjahat. Ia adalah produk zamannya: lahir dari ketimpangan struktural, hukum kolonial yang timpang, dan perlawanan lokal yang tidak terorganisasi secara politik. Ia mewakili suara masyarakat Betawi yang tidak tercatat secara resmi dalam sejarah, tetapi hidup dalam ingatan kolektif.
Dengan demikian, Si Pitung dipahami bukan sebagai legenda tanpa cela, melainkan sebagai figur historis yang dimitoskan, di mana fakta dan cerita rakyat saling bertaut. Ia adalah cermin dari Batavia kolonial—kota yang dibangun di atas ketertiban, tetapi juga perlawanan.