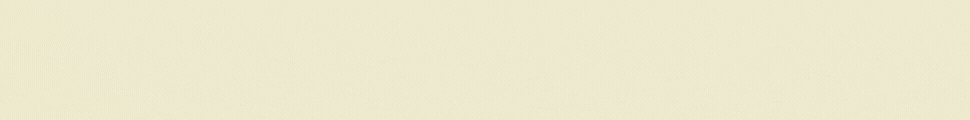NEGARA MEMBARA II : GARIS MERAH PARA PEJUANG
*
Malam menebar kelam, merayap di sela-sela deru angin yang membelai reruntuhan, seakan mengundang bayang-bayang untuk menyalakan bara kebimbangan di dada manusia.
Di tepi kali yang airnya keruh, sebuah gudang tua berdiri lunglai—dindingnya retak, atapnya bocor, dan pintunya nyaris terlepas dari engsel besi yang sudah berkarat.
Lampu minyak satu-satunya memancarkan cahaya kuning keemasan, menciptakan gerak bayangan yang menari liar di antara kayu lapuk dan drum kosong.
Empat sosok duduk menekuk di lantai berkerikil: Saka Negara, wajahnya teduh namun penuh ketegangan; Rima, matanya tajam menelisik setiap sudut; Halim, bibirnya tercekat menahan gelisah; dan Diman, enggan menunjukkan rasa takutnya meski tangan kanannya gemetar menahan minyak lampu.
Di tengah mereka terbentang peta besar Jakarta—torehan tinta yang sudah luntur, bekas lipatan yang menandai rute pelarian, titik pasukan penjajah, serta catatan rahasia yang baru mereka selundupkan lewat Hendrawan.
Saka mengangkat setangkai pena bambu dan membuka buku catatan di pangkuannya. Setiap coretan melengkung rapi, seolah tangan penulisnya menari dalam bisu, menuliskan harapan dan jebakan dalam satu tarikan garis.
“Informasi ini bisa jadi kunci untuk membalik keadaan. Pasukan Jepang mengendur setelah Bom Hiroshima, tapi mereka masih menancapkan taring di kota ini,” ucapnya pelan, suaranya bergetar tipis menandai ketidakpastian.
Rima menutup jarak, mencondong tubuhnya. Cahaya lampu memantul di kelopak matanya, menekankan setiap kerutan waspada. “Tapi motif Hendrawan masih kita ragukan.
Dia muncul dengan seragam samurai palsu, menandatangani komitmen tanpa saksi. Apakah ia benar-benar sekutu, atau sekadar pion dalam strategi musuh?”
Halim menepuk peta dengan ujung jarinya, menelusuri garis-garis merah yang menandai patroli malam. “Kita tak boleh gegabah. Sekali kesalahan, para pekerja paksa akan jadi tumbal, dan jejak kita terputus selamanya.” Suaranya pelan, seperti desir angin yang berbisik di celah dinding.
Diman menoleh, mencoba menebar senyum meski bening matanya memperlihatkan ketegangan tak terbendung. “Biarkan aku yang membawa perbekalan. Peluru buatan sendiri ini sudah kita uji di hutan belakang desa—mereka meledak sempurna, cukup membuat kekacauan.”
Sesaat hening, hanya detik jarum jam yang berdenting nyaring, seolah menertawakan rencana-rencana manusia. Di luar gudang, deru mobil patroli mereda, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih mencekam daripada dentuman bom.
Saka menutup buku catatan, menekankan ujung pena di bibirnya. “Kita hanya punya satu malam untuk memastikan: apakah Hendrawan benar-benar pembawa kabar kemenangan, atau sekadar bayangan yang memerangkap kita dalam kegelapan.”
Rima mengangguk perlahan. Dia menatap lembut ke arah Saka, lalu menoleh ke Halim dan Diman. “Kita bergerak tiga jam lagi, pada tengah malam. Diman akan menyusup sebagai pekerja paksa—kita sudah memiliki seragam dan tanda pengenal palsu.
Halim dan aku masuk dari pintu belakang, mematikan patroli listrik, lalu kau, Saka, masuk lewat kanal kecil di sisi utara gudang.”
Saka menarik napas panjang, lalu secara mengejutkan menimpali, “Tunggu—aku masih mendapat petunjuk lain dari catatan ini.” Dia membuka halaman kedua, memperlihatkan simbol-simbol aneh: lingkaran, pilar, bintang tiga. Rima memiringkan kepala, menyipitkan mata. “Apa ini?”
Dengan suara berbisik, Saka menjelaskan, “Ini bukan peta biasa. Hendrawan juga menuliskan koordinat bayangan—jalur rahasia di bawah tanah, gua kuno yang dipakai laskar terdahulu. Kalau benar, kita bisa memintas gudang, mengambil amunisi tanpa terdeteksi.”
Detik-detik berikutnya diwarnai tatapan saling menimbang antara keyakinan dan keraguan. Di antara reruntuhan yang menganga dan lampu minyak yang berkedip, empat sahabat saling bertukar janji—jika ini jebakan, maka mereka akan hadapi bersama. Jika ini kemenangan, maka mereka akan berjaya bersama.
Mereka bangkit, menebar senyum tipis, namun otot-otot tetap tegang. Rasa gelisah menuntun langkah mereka keluar gudang, menapaki jalan becek di samping kali.
Lilin di kantong Rima hampir padam, tertiup angin dingin malam. Suara gemerincing rantai sepatu karet Halim bergema di tanah berlumpur. Di kejauhan, lampu-lampu penjaga berpendar samar.
Ketika bayangan mereka memanjang di dinding gudang, satu hal jadi pasti: malam ini, tak hanya peta yang akan mereka jelajahi, tapi juga misteri motif Hendrawan—di antara cahaya redup dan kegelapan yang siap menelan setiap nyawa yang terlalu percaya.
Dan di setiap langkah, gema denting jarum jam terus mengingatkan: waktu semakin menipis, rahasia semakin mendesak, ajal bisa datang tanpa kabar.
**
Kilau rembulan terselip di sela tiang kayu gudang tua, menyorot permukaan besi yang terkikis karat. Tiga jam setelah pertemuan rahasia, Saka Negara, Rima, Halim, dan Diman telah menyamar: wajah ditutupi arang, tubuh menyatu dengan barisan pekerja paksa yang menggulung peti kayu besar berisi amunisi. Angin malam merambat dingin, namun keringat dingin tetap menetes di pelipis mereka.
Saka mengintip dari balik tumpukan drum minyak, merasakan detak jantungnya memecut. Di tangan kirinya tergenggam kertas koordinat Hendrawan—peta bayangan lorong rahasia.
Sinyal tangan tiba: satu ketukan di dada berarti “siap”, dua ketukan “mulai”. Rima, di sudut selatan gudang, menahan napas sambil membuka klip kawat tipis; cukup untuk memutus arus listrik.
Di lantai atas, Halim dan Diman bergerak bak bayang-bayang. Halim menyelinap naik tangga reyot, melancarkan potongan kawat ke panel saklar utama.
Dalam detik yang teredam, deru mesin mati, lampu meredup, menciptakan lorong gelap. Diman, berlagak sebagai “pekerja baru”, memancing perhatian penjaga dengan obrolan kikuk—tawa yang dipaksakan namun berhasil mengalihkan tatapan.
Secepat angin, Saka menyusup ke dalam gudang utama. Jejak kaki tertatih di balok lapuk saat ia membuka tumpukan kotak berisi peluru dan bom molotov.
Menyingkap lantai kayu di bawah palang besar, ia menemukan lubang kecil—gerbang ke lorong bawah tanah. Dengan hati-hati, ia merayap masuk, tubuhnya berselimut lembap dan pekat.
Di bawah tanah, udara pengap berbaur dengan bau lumut. Tetesan air merintih di dinding batubara purba, memantul menjadi gema yang menghantui.
Rima mengikuti, menyalakan senter kecil yang cahayanya menari di relief kuno: lingkaran-lingkaran ritual dan alur batu terukir. “Ini jalur bayangan, Saka,” bisiknya. “Hendrawan tak sekadar curi amunisi—ia buka jalan yang terlupakan.”
Sementara itu, di permukaan, Halim menyusun bom asap rakitan Diman—silinder kecil berisi bubuk pekat. “Tiga… dua… satu…” gumamnya, lalu melempar bom ke lantai gudang. Ledakan asap membubung, melingkupi pekerja dan penjaga dengan kabut tebal.
Suara langkah panik, rantai peti beradu benturan—semua teredam kabut pekat. Rima dan Diman menyingkirkan penjaga ke sudut, mencegah mereka menghalangi rute evakuasi.
Detik kemudian, Saka dan Rima muncul dari bawah tanah, bahu mereka memikul dua peti amunisi berat. Adrenalin mengalir deras, otot mereka tegang menahan beban.
Di balik kabut, sosok tiba-tiba muncul: Hendrawan, berdiri tegap dengan seragam Jepang compang-camping.
Matanya menyorot di antara kepulan asap. “Kalian terlalu berisik,” ujarnya dingin. “Namun kalian sampai ke tujuan. Ambil amunisi ini—perlawanan sejati dimulai sekarang.” Ia mengulurkan tangan seolah memberkati aksi mereka.
Saka melangkah maju, napas terengah. “Mengapa kau di sini, Hendrawan? Tunjukkan kesetiaanmu.” Hendrawan tersenyum tipis, mengetuk peti di tangan Saka. “Aku agen ganda. Informasi ini kutip dari markas pusat—termasuk peta bawah tanah kuno.
Selain amunisi, kubawa data patroli dan posisi artileri mereka.” Rima memicingkan mata, ragu namun terpikat oleh janji kemenangan.
Tiba-tiba, gemuruh tank mendekat pintu utama. Lampu sorot memutar mencari sumber asap. “Waktu kita hampir habis!” teriak Saka. Bersama, mereka menyeret peti ke lorong, samar tertutup kabut.
Lorong berbelok, membawa mereka ke ruang bawah tanah luas tempat Delman menunggu dengan gerobak kayu. Tanpa sepatah kata, Delman menggeser peti ke dalam gerobak, menutup terpal, lalu meniup peluit pendek—sinyal evakuasi. Satu per satu, pejuang merayap keluar, menapaki bebatuan licin menuju celah pintu kayu.
Di atas tanah, mereka membaur bersama para pekerja paksa. Lampu sorot musuh berputar tanpa hasil; tank mundur. Suara gemuruh pasukan pembersih mereda, sementara para pejuang menghilang dalam pelukan malam.
Ketika langkah mereka memudar di jalan becek, bulan memantul di air kali keruh. Saka menoleh, matanya memendam kegelisahan. “Malam ini kita menang—tapi bayang-bayang kebenaran masih menunggu,” gumamnya. Rima menggenggam lengannya, tekad membara. Perlawanan di balik kabut baru saja dimulai.
***
Malam masih lengket di udara ketika gemuruh langkah pasukan Jepang menggema di parit sempit—puluhan tentara berpakaian serba abu-abu, senapan terangkat siap memuntahkan peluru.
Di balik rerimbunan semak, Saka Negara mengatur napas, menatap wajah teman-temannya: Rima menggenggam bayonet dengan tangan gemetar, Halim menekan ramuan asap di saku, dan Hendrawan—meski luka di bahu basah darah—tetap tersenyum tipis memberi semangat.
Dari atas bukit kecil, Jenderal Nakasima berdiri tegap memerhatikan amunisi yang terpajang di hadapannya. Di sisinya, Hirata, asisten setianya, mengulurkan teropong dan mencatat setiap pergerakan kaum pejuang.
“Laporanmu,” bisik Nakasima. Hirata menunduk, lalu menatap medan perang: “Mereka hanya lima orang, Yang Mulia. Namun berjilid keberanian—berbahaya, jika dibiarkan.” Nakasima mengetuk gagang pedang, mata elangnya kilat menandai ketegasan:
“Hentikan mereka di sini, sebelum kabur ke perkampungan. Tembak tanpa ampun.”
Tiba-tiba, dari reruntuhan gudang tua, sosok setengah baya muncul—mantel lusuh menutupi punggungnya, topi petani meneduhkan wajah yang berkerut oleh waktu.
Tanpa aba-aba, ia menyalakan lampu lentera kecil dan melompat turun ke jurang; kilatan mata tajamnya lebih erat dari senjata. “Ikuti aku,” geramnya pelan, langsung menarik tangan Jatmiko, mahasiswa idealis yang sejak awal berjuang di samping Saka.
Saat itulah peluru pertama meletus—ledakan keras menghantam dinding batu, menimbulkan cipratan tanah. Jatmiko mengangkat senjatanya, membalas dengan tembakan terarah. “Gawat!” teriak Halim, melempar bom asap yang telah diramu.
Kabut pekat menutup sebagian area, namun lensa teropong Hirata tak terpengaruh: ia memberikan kode ke unit bayangan, mendekatkan barisan infanteri.
Jatmiko kini berada di depan, menyapu area dengan korekapi peluru. Di dadanya tertancap selempang bertuliskan nama “Jatmiko”, bukti semangat juangnya. Ia menatap Saka sekejap, alisnya mengerut: “Terus maju!” Namun sebuah deru mendadak dan peluru merobek udara—tubuh Jatmiko tersentak, menunduk.
Rima berlari ke sisinya, tangan terulur mencoba menahan darah yang mengalir deras dari paha. “Jat…” Rima terisak. Jatmiko terkulai, matanya menatap samar ke langit, lalu tersenyum getir: “Bang…kitkan…api…” Suara terakhirnya hampir tenggelam di dentum senjata, lalu ia terjatuh, napasnya terhenti.
Saka menjerit, berlari menyalib rerimbunan, meraih tubuh sahabatnya. Darah Jatmiko meresap ke tanah becek, bunga-bunga kecil di pinggiran parit terbenam dalam darah. Hendrawan menunduk, berdiri sambil menekuk lutut—matanya berkaca. “Maafkan aku, bro,” bisiknya pelan, menutup mata Jatmiko.
Dalam kekalutan itu, sosok paruh baya misterius memanggul tubuh Jatmiko, membawa ke balik semak tebal. “Secepatnya aku cabut pelurunya,” gumamnya, lalu menghilang di kelokan bayangan. Saka menoleh, napasnya memburu, kenangan tawa Jatmiko membekas di kalbu.
Tapi pertempuran belum usai. Puluhan pasukan Jepang menerjang, senapan siap tembak. Saka mengangkat senapan, sudut bibirnya mengeras. “Hendrawan, Rima, ikuti jalur sempit—kita pecah formasi!” perintahnya. Mereka menyelinap ke lorong gelap di tepi parit, suara kaki bertalu dinding batu menandai kedekatan musuh.
Tiba-tiba, kilatan pedang di tangan sosok paruh baya menari di depan mereka—ia kembali, menebas satu tentara yang mendekat; bunyinya seperti cuit api di malam senyap. “Maju!” ia memekik, kemudian memberi sambaran cahaya lentera ke wajah Saka: kerut di pelipisnya tampak menganga, namun mata mereka bersatu tekadnya.
Dengan ledakan asap kecil dari Halim, kawanan Jepang terdesak mundur; dentuman granat tangan bergema, menyalakan bara api di rerumputan kering.
Para pejuang menerjang, api keberanian menyala saat mereka membalas tembakan. Namun musuh tak mudah surut—barisan infanteri menahan maju, payung mortir bergemeretak menembus tanah.
Hirata, di puncak bukit, mengangkat bendera kecil—sinyal cadangan merapat. Saka menatap langit kelam, seolah berteriak memanggil bumi bergetar. Rima menembakkan pistol satu per satu ke arah bayangan baret putih, suara “tek” tiap peluru pecah di udara.
Hendrawan menjatuhkan badan, memasang ranjau kecil di atas parit; “Hitung mundur,” gumamnya, lalu ia berlari langsung menuju sayap musuh, meledakkan ranjau; teriakan kepanikan menyusul.
Hujan peluru dan asap mendidih, bebat bayangan dan kilatan api bersaing menerangi malam. Saka meraih tubuh rekan terakhir, menotok detak jantung yang hampir padam.
Ia berbisik di telinga Hendrawan: “Bertahan sampai fajar…” Namun di kejauhan, bayu fajar mulai merona—pertanda malam akan pergi, dan musuh siap memberi serangan pamungkas.
Di balik teriakan pertempuran, sosok paruh baya itu menghilang sekali lagi, meninggalkan Saka dan kawan-kawan dalam kobaran peperangan.
Dalam setiap dentuman meriam dan gemuruh terompet panggilan mundur, satu hal pasti: jiwa Jatmiko dan keberadaan misterius lelaki tua itu akan menjadi pelita—atau bayang-bayang yang tertinggal di medan perang hati mereka.
****
Malam menebal di atas reruntuhan desa kecil ketika Saka Negara berdiri terpaku, pantatnya menempel dingin di dinding bata yang retak. Cahaya bulan menembus celah atap gudang, memantul kilau di pisau belatinya yang sudah berlumuran darah.
Sekelompok puluhan tentara Jepang—dipimpin Nakayama dan Hirata di belakang barisan—mendekat perlahan, derap sepatu boot menggetarkan tanah becek.
Saka menoleh, melihat Rima bersandar lemah pada tumpukan kayu, napasnya serak menahan sakit akibat pecahan peluru. Di sampingnya Halim, tangannya gemetar, bom asap kosong di genggaman.
Hendrawan, walau luka parah di bahu, masih mencoba menambal kain pelindungnya, anime derap peluru membuatnya terpincang. Mereka terpojok; satu-satunya celah pelarian tertutup kawanan musuh.
“Majulah!” teriak Nakayama, melontarkan semangat barbar. Sebuah mortir meledak di dekat parit, menyemburkan tanah dan pecahan kayu ke tubuh para pejuang. Saka mengelak cepat, berdiri sempurna, belati kecil di tangan kirinya berputar seperti bayangan.
Dengan kecepatan lincah, ia menerjang dua prajurit paling depan—pisau meluncur ke leher satu, lalu menusuk selangka yang menahan senapan prajurit lain. Darah memercik di jalan licin, tapi ia tak sempat menoleh; langkahnya sudah memutar, menebas pantat dada prajurit ketiga yang hendak membidik.
Rima merapat, menembakkan pistol rebutan yang sempat ia selipkan—tik… tik… peluru melesat tepat ke helm musuh hingga retak. “Aku masih kuat!” bisiknya, keyakinan memenuhi nada suaranya.
Halim berlari menjemput bom cadangan, menaburkan sisa asap putih di kaki tentara yang berteriak tersedak. Kabut mengepul, menutupi pandangan musuh, tapi Saka tahu jarak itu hanya sementara. Di tengah hujan peluru, mereka bakit melatih adrenalin.
Namun musuh tak mudah ditundukkan. Hirata, dengan pedang serupa samurai yang melayang di tangan, berkelebat ke samping, menahan tebasan belati Saka dengan hujung pedangnya.
Percikan gesekan logam bersahut, sinar lentera jarak jauh berpendar di sela asap tebal, menyorot kilau kepulan peluh di wajah Saka. Tiap detik terasa seperti menit, medan perang mengecil menjadi satu ruang sempit di mana cuma ada nyawa dan pertempuran.
Saat kehabisan ruang, Hendrawan terhuyung, terjatuh menahan napas—sekali hentakan granat mengguncang lantai, menembus tulang kakinya. Ia meratap pelan: “Saka… lari… jangan…” Tetapi Saka menggenggam lengan Hendrawan, matanya meleleh di cahaya rembulan: “Kita tak bisa tinggalkan kau!” Ia menendang beberapa prajurit yang menjarah tubuh Hendrawan, lalu menarik sahabatnya ke balik reruntuhan.
Dalam kebuntuan itu, suara serentak bergema di kejauhan—deru senapan mesin ringan, tembakan berirama diiringi teriakan “Merdeka! Allahu Akbar!”. Ajaibnya, bayang-bayang hitam di seberang parit bergeser; puluhan pejuang Indonesia, berseragam lusuh dan bertuliskan kain merah-putih di lengan, menembus kabut.
Di depan barisan, berdiri sosok tegap berwajah keras: Kapten Halir Mangundjidjadja, mata perangnya berapi, pedang komando di tangan kanan, pistol serbu di tangan kiri.
“Kawan-kawan! Majulah!” bentak Halir, suaranya menembus riuh pertempuran. Gelombang pasukan bantuan menerjang seperti ombak raksasa: tembakan dari senapan Lee-Enfield, dentuman mortir buatan sendiri, granat tangan yang dilempar bergantian.
Jepretan tembakan dan ledakan granat mewarnai udara, memecah formasi Jepang. Puluhan prajurit Nakayama terperangkap, panik, dan rebah satu per satu di tanah berlumpur.
Lentera-gantung di reruntuhan gudang meledak, menyemburkan api jingga ke langit malam. Halir menerjang, pedangnya menebas serdadu di depannya—kilatan baja memisahkan kepala helm dari bahu.
Rima dan Halim menelan keberanian baru, membantu menggempur sayap kanan musuh. Saka, dibantu beberapa pejuang baru, mengambil posisi sempit, menebas dan menahan mundur; setiap tebasan belati kecilnya menancap di urat leher, memecah kesunyian malam dengan gemuruh dentuman darah.
Nakayama melihat barisan kendur; ia mengibaskan tangan, memerintahkan mundur. “Beri ruang! Mundur cepat!” komandonya menggema, sementara Hirata membenteng diri di belakang, menembakkan pistol naga—semburan peluru panas melelehkan karat di dinding.
Namun barisan bantuan Indonesia tak tergoyahkan: ledakan ranjau kecil memecah kaki para penjaga mundur, rintihan nyawa menyambut gelombang pasukan Merah Putih.
Dalam keremangan asap dan lampu lentera, Saka berdiri tegap—pisau belatinya berdarah, dada berdenyut cepat. Ia menatap Nakayama yang beringsut naik kuda bayangan di ujung jalan.
Pistol Saka menepuk mata sang jenderal: sebuah tembakan terarah menembus pelana kuda, membuat Nakayama terhuyung. Tanpa menunggu, pejuang Indonesia menyerbu, menaklukkan sisa pasukan Jepang, memastikan mereka tak lari selangkah pun lebih jauh.
Ketika fajar mulai merona samar di ufuk timur, tanah becek di medan laga dipenuhi tubuh-tubuh pejuang—Indonesia dan Jepang—tanpa membeda-bedakan darah yang mengalir. Kapten Halir menegakkan diri, nafasnya berat namun penuh kemenangan.
Ia mengangkat tangan, memanggil Saka dan kawan-kawan: “Kita selamat! Berkat keberanian kalian!” Saka menunduk, menaruh pisau belati kecilnya ke samping, lalu menatap rekan-rekannya—Rima, Halim, Hendrawan yang masih merintih, dan jenazah Jatmiko yang disemayamkan dengan khidmat di tanah perang.
Di kejauhan, matahari pertama mencipratkan sinar kemerahan di awan, menandai akhir malam perjuangan dan awal harapan baru. Meski kehilangan banyak saudara, Saka tahu bahwa dengan kedatangan Kapten Halir Mangundjidjadja dan pasukannya, api perlawanan tak akan pernah padam.
Dan bila bayangan kegelapan kembali datang, jiwa-jiwa penuh darah ini siap menebasnya—satu tebasan belati kecil untuk setiap nyawa yang gugur demi kemerdekaan.
*****
Saka Negara menghela napas panjang saat kakinya menginjak halaman markas pejuang—deretan barak kayu dan tenda lusuh berjajar rapi, lampu minyak berkelip pelan di setiap sudut. Rima dan Halim menyusul di belakang, membawa karung amunisi dan tong air panas untuk meredam luka.
Di udara tipis senja, riuh rendah percakapan para pejuang mewarnai kebekuan hati Saka—namun ada satu pintu kayu besar yang sejauh ini tetap tertutup untuknya.
“Rima… Halim…” suara Saka pelan, menahan getar. Keduanya menoleh. “Di mana dia? Sosok yang membantu kita?” tanyanya, mata menelisik setiap bayangan di antara barak.
Rima meraba leher bajunya, jari-jarinya menggeliat di bawah kain arang. “Aku belum melihatnya muncul lagi,” jawabnya lirih. Halim menunduk sejenak, lalu menegakkan badan. “Aku dengar kabar dia menghilang ke lorong senjata—tapi tak seorang pun berani mengejarnya. Katanya, dia menjaga jarak.”
Saka mengangguk, dadanya mengencang. Ia menatap ke arah gudang persenjataan di tepi barak: pintu setengah terbuka, nyala api unggun kecil menari di dalam. Namun dari situ ia tak melihat bayangan apa pun, kecuali deretan senjata dan perlengkapan—semua berderet diam menunggu aksi selanjutnya.
Sementara itu, jauh di balik bukit keramat di utara, sosok lelaki paruh baya berdiri tegap. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, ikat pinggang kain merah melingkar di pinggangnya—satu-satunya warna mencolok di sela debu dan reruntuhan.
Di tangannya tergenggam lentera kecil yang berpendar temaram, menyingkap wajahnya dari balik topi kain. Matanya yang tenggelam di kerut waktu menatap lurus ke selatan, arah markas pejuang, namun tanpa seorang pun di sana yang tahu ia berada di situ.
Dalam hening yang menusuk, lelaki itu bergumam pelan—suara nyaris tersedak angin dingin malam:
“Kuharap kau tak perlu menebas belati kecilmu lagi, cucuku. Janjiku pada Raden Arya Saka tetap terpatri; bila nyawamu terancam, aku akan datang…”
Ucapannya terhenti, tertelan gemerisik ranting dan desir angin malam. Ia menoleh sekali ke bayangan pepohonan, seakan ragu apakah langkah berikutnya akan mengaburkan garis waktu.
Namun tatapannya kembali tertuju pada cahaya kecil di ujung lembah, di mana Saka dan kawan-kawan memasuki pintu barak tanpa menyadari mata yang tak tampak itu menerawang setiap gerak mereka.
Di dalam markas, Saka menatap langit yang mulai gelap; bintang-bintang malu-malu menampakkan diri. Rima mengusap peluh di dahinya, mencoba memberi semangat. “Istirahatlah dulu,” bisiknya. “Besok kita susun rencana serangan.” Halim menyiapkan periuk teh hangat untuk membalut tubuh pejuang yang kedinginan.
Tetapi Saka hanya terdiam, menolak duduk. Pikirannya melayang pada suara bergumam di kejauhan—janji tak terucap yang hanya didengar oleh angin. Ia menelusuri ruang pertemuan kosong, meja panjang bekas rapat tertutup kain kasar, kursi-kursi kayu berderak. Sekali lagi ia bertanya pada keheningan:
“Di mana dia…?”
Di puncak bukit, sosok itu menunduk, menutup mata sesaat. Seketika, angin bertiup kencang, membawa bisikan pepohonan menari di udara malam. Lelaki itu mengangkat lentera lebih tinggi, memetak jalan pulang ke lorong-lorong waktu yang hanya ia kuasai.
Ia tak melangkah mendekat—sebab peranannya tak untuk muncul di hadapan cucu yang masih menebas jalan di medan gerilya. Cukup baginya memastikan bahwa, kapan pun Saka benar-benar terhimpit, janji untuk menjaga keselamatannya akan menuntun jejaknya menembus waktu, menyelamatkan tiap helaan napas yang nyaris terhenti.
******
Senja merunduk di balik perbukitan Jakarta yang porak-poranda, membiarkan lembayung keemasan terhampar lembut di ufuk barat. Markas pejuang kini tenang, save ‘perang dalam bayang-bayang’ mereda sejenak berganti tatapan pilu dan harapan.
Di tengah barak kayu, Saka Negara berdiri mematung, menatap bendera Merah Putih yang berkibar pelan—setelah darah dan air mata, kini tugas utama mereka bukan hanya menahan serangan, melainkan membangun kembali harapan yang hampir terkubur.
Rima menyalakan api unggun, membakar dedaunan kering sebagai penghormatan bagi para sahabat yang gugur. Aroma kayu bakar menyelimuti udara lembap; setiap kepulan asap seolah mengangkat doa bagi Jatmiko dan ratusan pejuang lain yang berkurban nyawa demi kemerdekaan.
Halim menyibakkan kain penutup jenazah Jatmiko, lalu menancapkan bunga melati putih di sisi peti—bunga yang pernah mereka panen bersama di desa, simbol ketulusan dan pengorbanan.
Di lorong senyap markas, sesosok bayangan bergerak perlahan. Sosok lelaki paruh baya itu—pelindung tanpa nama—mengendap ke ambang pintu gudang senjata, menoleh sekali ke kumpulan pejuang yang tengah berkumpul.
Ia tidak menyapa, hanya melemparkan tatapan singkat pada Saka dari kejauhan. Dalam senyap, janji lama diucapkan kembali dalam hati:
“Aku akan selalu menjaga, kapanpun engkau terdesak.”
Tanpa satu kata pun, ia menghilang ke balik bayangan barak, kembali ke tempat tak kasat mata bagi mata manusia biasa—di mana waktu dan ruang bergeser menurut kehendaknya. Jejaknya tertinggal dalam kerlip lentera yang meredup, mengilhami rasa aman sekaligus tanda tanya yang tak kunjung terjawab.
Saka menutup mata, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Di balik nafasnya, ia meneguhkan tekad: perjuangan belum selesai. Habis magrib besok, mereka akan kembali bergerak—menyusup ke barisan musuh, menggalang hati sanak, dan menyalakan semangat baru di medan laga.
Namun sebelum itu, malam terakhir di markas ini akan mereka manfaatkan untuk merajut persaudaraan, meracik strategi, dan memberi penghormatan terakhir pada para pahlawan yang telah gugur.
Fajar nanti akan membawa pelangi baru—cahaya kemenangan yang perlahan menyinar setelah lorong-lorong gelap terlewati. Dan meski bayangan waktu itu masih mengintai di tepian, Saka tahu ia tak pernah benar-benar sendiri.
Di setiap hembusan napas, ia merasakan kehadiran sosok pelindung misterius, janji suci yang menembus masa: bahwa di saat terjepit, seorang kesatria tak akan pernah kehilangan harapan, sekalipun ia harus menebas gelap demi membebaskan cahaya.
BERSAMBUNG!
DISCLAIMER: *Kisah ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari sejarah dan imajinasi kreatif. Seluruh karakter, kejadian, dan alur cerita adalah hasil rekaan yang tidak secara langsung mewakili individu atau peristiwa nyata.
*Naskah ini disusun berdasarkan berbagai sumber terpercaya dengan pengolahan redaksional oleh tim PesonaDunia.Com. Untuk informasi selengkapnya, silakan merujuk pada tautan sumber (Source News) yang disertakan.